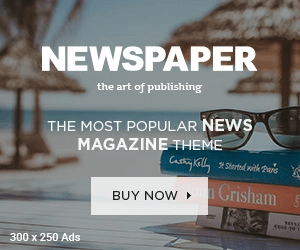Oleh : Andi Pramaria
Nusa Tenggara Barat adalah provinsi yang kaya akan sumber daya alam. Sektor pertanian menyumbang lebih dari 22% terhadap PDRB, sementara tambang emas dan tembaga di Pulau Sumbawa menyumbang sekitar 17%. Selain itu, NTB memiliki laut seluas 2,9 juta hektare dengan potensi perikanan yang besar, serta keindahan alam dan budaya yang menjanjikan sebagai destinasi wisata kelas dunia. Dengan semua potensi ini, NTB seharusnya bisa menjadi daerah yang makmur.
Namun kenyataannya, NTB masih menghadapi tingkat kemiskinan yang tinggi. Menurut data BPS tahun 2024, angka kemiskinan mencapai 13,85%, jauh di atas rata-rata nasional. Secara nominal, jumlah penduduk miskin lebih dari 700.000 jiwa. Bahkan daerah seperti Sumbawa Barat, yang menjadi lokasi tambang besar PT Amman Mineral Nusa Tenggara, tetap mencatat angka kemiskinan yang signifikan. Jika menggunakan standar Bank Dunia sebesar US$8,30 per kapita per bulan (sekitar Rp1.512.000), maka jumlah penduduk miskin akan jauh lebih besar. Sebagai gambaran, seorang PNS dengan satu istri dan dua anak membutuhkan pendapatan minimal Rp6.048.000 per bulan agar tidak tergolong miskin menurut standar tersebut.
Kemiskinan di NTB bukan hanya soal angka, tapi juga soal struktur dan arah pembangunan. Ada empat jenis kemiskinan yang terjadi: kemiskinan struktural akibat kebijakan yang tidak berpihak, kemiskinan mutlak karena pendapatan di bawah garis kemiskinan, kemiskinan relatif karena ketimpangan antar kelompok, dan kemiskinan kultural yang dipengaruhi oleh tradisi konsumtif seperti pesta pernikahan dan ritual adat yang menguras biaya.
Ada lima faktor utama yang memperkuat paradoks ini. Pertama, sebagian besar SDA NTB diekspor dalam bentuk mentah tanpa pengolahan. Contohnya, ekspor jagung 6.000 ton ke Filipina tanpa diolah menjadi pakan ternak menyebabkan hilangnya nilai tambah. Jika diolah, nilai ekonominya bisa mencapai Rp100 miliar, dengan keuntungan bersih sekitar Rp30 miliar. Kedua, perusahaan besar enggan melakukan transfer teknologi kepada tenaga kerja lokal. Akibatnya, masyarakat hanya menjadi buruh kasar dan tidak memiliki keterampilan teknis. Ketiga, daerah yang kaya SDA justru tertinggal dalam hal infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan pendidikan. Keempat, NTB terlalu bergantung pada sektor tambang dan pariwisata yang rentan terhadap krisis. Sektor pertanian yang stabil belum dikembangkan secara maksimal. Kelima, lemahnya tata kelola dan regulasi menyebabkan kebocoran keuntungan dan kerusakan lingkungan. Pertambangan rakyat ilegal banyak merusak alam, sementara pemerintah belum memberikan pembinaan dan perizinan yang memadai.
Dampak sosial dari kondisi ini sangat nyata. Banyak warga desa yang pindah ke kota atau menjadi pekerja migran ke luar negeri, terutama perempuan. Tekanan ekonomi juga menyebabkan banyak anak putus sekolah dan terjadi pernikahan dini. Konflik agraria dan perebutan lahan semakin sering terjadi karena ekspansi investasi yang tidak memperhatikan hak masyarakat adat dan petani.
Untuk mengatasi semua ini, NTB perlu mengubah pendekatan pembangunan. Hilirisasi industri harus didorong agar hasil tambang, pertanian, dan perikanan bisa diolah di daerah sendiri. Masyarakat sekitar SDA harus diberdayakan, bukan hanya dijadikan objek program CSR. Pendidikan dan pelatihan vokasional perlu diperkuat agar SDM lokal bisa bersaing dan menjadi pelaku utama dalam pengelolaan SDA. Tata kelola SDA harus transparan dan berpihak pada masyarakat lokal. Selain itu, ekonomi alternatif seperti pariwisata desa, ekonomi kreatif, dan koperasi komunitas harus dikembangkan agar tidak terlalu bergantung pada sektor ekstraktif.
Salah satu strategi yang menjanjikan adalah penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Jika koperasi ini bisa berjalan dengan baik, maka akan menjadi agen perubahan ekonomi desa. Koperasi bisa menjadi penyedia kebutuhan masyarakat, distributor produk desa ke kota, mitra Bulog, dan pengelola SDA yang berkeadilan. Fungsi koperasi yang terbuka dan fleksibel bisa menjadi sarana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA secara inklusif.
Kemiskinan di tengah kekayaan alam adalah ironi yang menyakitkan. NTB punya semua syarat untuk menjadi provinsi maju. Yang dibutuhkan adalah perubahan paradigma: dari eksploitasi menuju pemanfaatan berkeadilan. Jika potensi lokal diberdayakan dan tata kelola diperbaiki, maka NTB bisa keluar dari kutukan sumber daya dan mewujudkan kesejahteraan yang merata.(*)